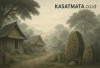Budaya Cancel Culture Apakah Ini Bentuk Keadilan atau Hanya Amarah Digital

Budaya Cancel Culture Apakah Ini Bentuk Keadilan atau Hanya Amarah Digital--screnshoot dari web
KORANRM.ID - Di era digital, keberadaan media sosial telah menjadi alat yang sangat kuat dalam menyuarakan pendapat, memperjuangkan keadilan, dan menegur perilaku yang dianggap tidak etis. Salah satu fenomena yang muncul dari kekuatan kolektif ini adalah cancel culture, yaitu praktik publik untuk memboikot atau mencabut dukungan terhadap tokoh publik, selebritas, atau bahkan merek, karena dianggap melakukan tindakan yang tidak pantas, kontroversial, atau melanggar norma sosial. Namun, di tengah geliatnya semangat "bertanggung jawab secara publik", muncul pertanyaan penting: apakah cancel culture benar-benar bentuk keadilan sosial, atau hanya luapan amarah digital tanpa kontrol?
Secara historis, cancel culture berakar dari gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, terutama di komunitas yang selama ini dimarjinalkan. Gerakan #MeToo, misalnya, menjadi tonggak awal bagaimana kekuatan suara kolektif di media sosial mampu membongkar praktik kekerasan seksual yang selama ini tersembunyi. Dalam kasus ini, praktik "cancel" menjadi alat untuk menegakkan akuntabilitas, terlebih ketika sistem hukum konvensional dinilai gagal memberikan keadilan yang memadai. Dengan begitu, cancel culture sering dilihat sebagai bentuk keadilan alternatif yang mampu menyoroti perilaku toksik yang tidak tersentuh hukum.

BACA JUGA:Kesepian di Era Digital Ketika Dunia Ramai, Tapi Hati Sepi
BACA JUGA:Digital Detox Mengapa Rehat dari Media Sosial Bisa Menyelamatkan Fokusmu
BACA JUGA:Transpormasi Pendidikan Era Digital
Namun, seiring perkembangannya, cancel culture tidak selalu bergerak di jalur keadilan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa orang bisa "di-cancel" hanya karena satu kesalahan masa lalu, lelucon lama, atau bahkan pernyataan yang dipotong dari konteks. Dalam situasi ini, internet sering bertindak sebagai hakim sekaligus algojo, tanpa ruang bagi klarifikasi atau proses yang adil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya budaya intoleransi terhadap kesalahan, di mana seseorang langsung "dihukum" tanpa kesempatan belajar dan memperbaiki diri.
Fenomena ini menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika kekuasaan dan opini publik. Terkadang, cancel culture justru digunakan sebagai alat untuk membungkam lawan ideologis atau menyerang pihak yang tidak sejalan secara politik. Misalnya, seseorang bisa "di-cancel" karena menyuarakan pandangan yang tidak populer, walaupun pandangan tersebut tidak melanggar hukum atau norma etika. Akibatnya, ruang diskusi menjadi sempit, dan masyarakat cenderung takut bersuara jujur karena khawatir menjadi target cancel culture. Hal ini tentu berbahaya bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi.
BACA JUGA:Gubernur dan Media Sosial Antara Gimik Politik dan Strategi Digital yang Efektif
Dampaknya pun tidak main-main. Banyak individu yang kehilangan pekerjaan, rusak reputasinya, bahkan mengalami gangguan mental akibat tekanan publik yang luar biasa. Apalagi dalam dunia maya yang tidak mengenal lupa, jejak digital bisa terus menghantui seseorang selama bertahun-tahun, meskipun ia telah meminta maaf dan berubah. Dalam beberapa kasus, hukuman sosial dari cancel culture bisa jauh lebih berat dari kesalahan yang diperbuat, bahkan melebihi sanksi hukum sekalipun.
Di sisi lain, ada juga argumen bahwa cancel culture dapat menjadi sarana edukatif bagi masyarakat. Ketika seseorang "di-cancel", diskusi tentang isu yang berkaitan sering kali muncul di ruang publik—entah itu tentang rasisme, seksisme, atau privilege. Dengan demikian, praktik ini bisa mempercepat kesadaran kolektif dan mendorong perubahan sosial. Akan tetapi, efek edukatif ini hanya tercapai jika prosesnya disertai ruang dialog, bukan hanya persekusi dan penghukuman.
BACA JUGA:Crypto AI Ketika Kecerdasan Buatan Mulai Mengatur Portofolio Digital Anda
Perlu dibedakan pula antara akuntabilitas dan pembatalan. Akuntabilitas melibatkan proses refleksi, permintaan maaf yang tulus, dan perubahan nyata. Sedangkan pembatalan cenderung bersifat final dan tidak memberi kesempatan kedua. Jika kita menginginkan masyarakat yang sehat dan inklusif, tentu kita perlu lebih mengedepankan proses edukatif dan pemulihan, bukan sekadar hukuman.
Di tengah semua itu, muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Media sosial harus menjadi ruang di mana suara kebenaran bisa didengar, tapi juga tempat di mana kesalahan bisa diperbaiki. Masyarakat perlu membangun budaya literasi digital dan empati, agar tidak terjebak dalam euforia massa yang bisa berujung pada penghakiman sepihak.
BACA JUGA:Laptop Aman dari Hacker 5 Kebiasaan Digital yang Harus Kamu Terapkan
Cancel culture pada akhirnya adalah refleksi dari dinamika masyarakat digital saat ini—cepat, reaktif, dan penuh tekanan. Ia bisa menjadi alat perlawanan terhadap ketidakadilan, namun juga bisa berubah menjadi senjata yang melukai siapa saja, bahkan tanpa proses yang adil. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak serta-merta ikut dalam arus massa, melainkan menimbang dengan bijak konteks, niat, dan proses pemulihan dalam setiap tindakan sosial yang kita lakukan di ruang digital.
BACA JUGA:Web3 dan Crypto Kolaborasi Teknologi yang Mendorong Era Digital Baru
BACA JUGA:Dari Manual ke Digital Transformasi Kepemimpinan Daerah di Era Teknologi
Referensi:
• Ng, E. (2020). "No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation". Television & New Media.
• Beyer, C. (2021). "The Ethics of Cancel Culture: Retribution, Accountability, or Mob Justice?" Journal of Media Ethics.
• Kompas.com. (2023). "Cancel Culture: Gerakan Keadilan atau Penghakiman Publik?"
• The Atlantic. (2022). "The True Cost of Cancel Culture: Can Anyone Recover?"
• Tirto.id. (2024). "Mengapa Cancel Culture Bisa Jadi Boomerang Bagi Kebebasan Berekspresi"